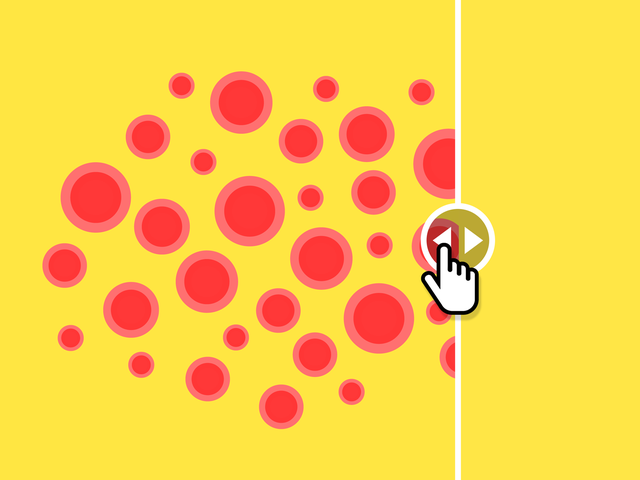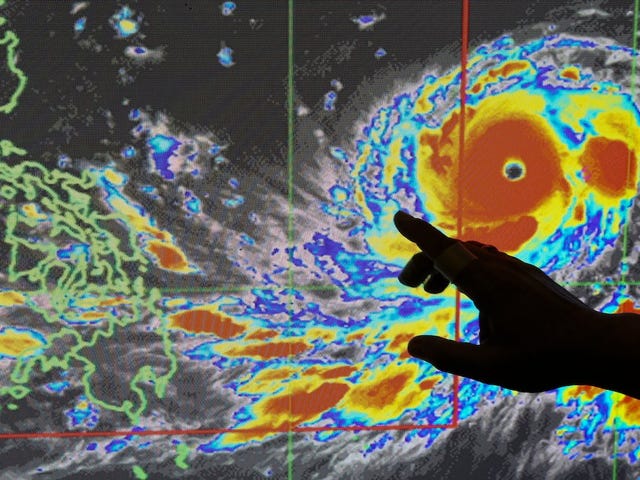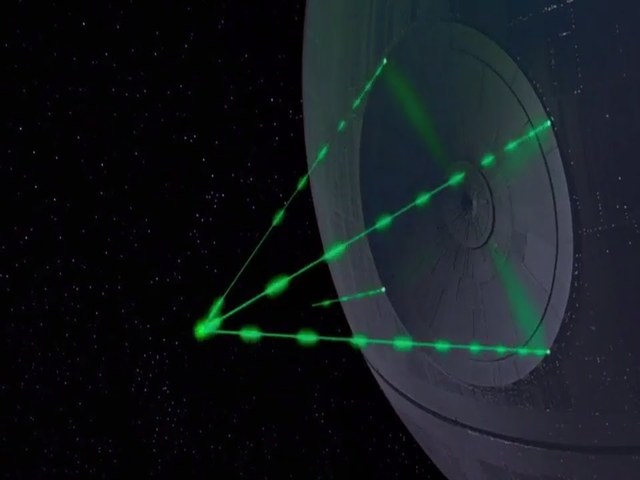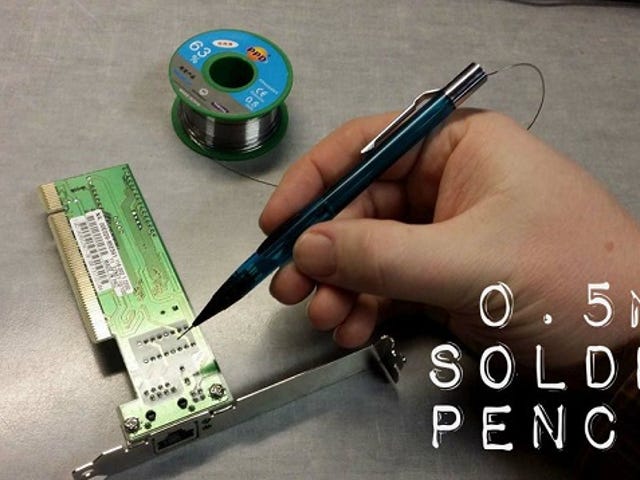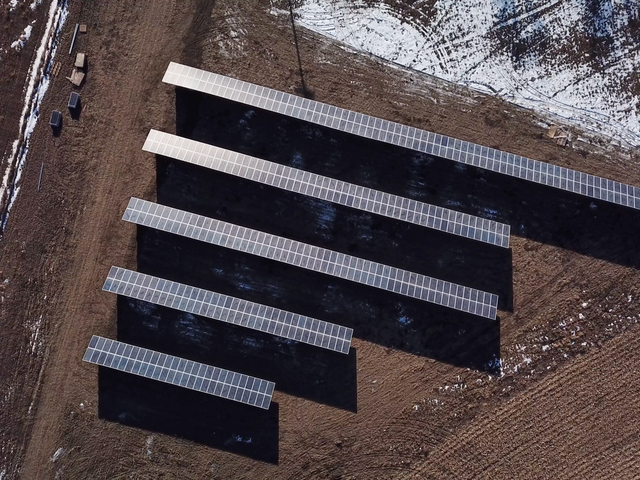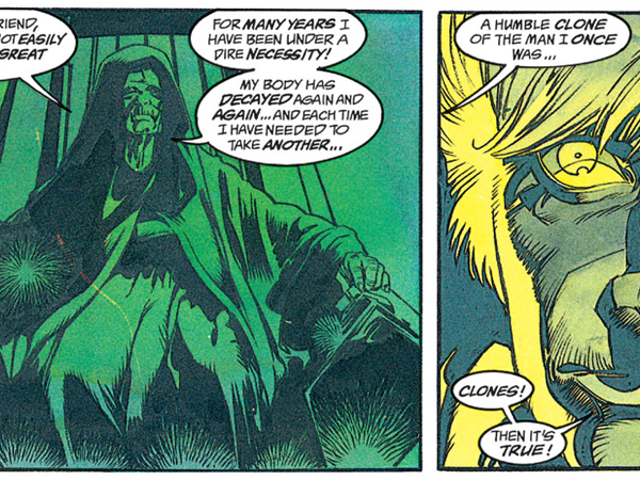Dengan The Hand Of God, sutradara The Great Beauty dengan hangat mengunjungi kembali masa kecilnya

Ketika Diego Maradona memimpin tim Argentina meraih kemenangan di Piala Dunia 1986, itu bukan pertandingan terakhir dan penuh kemenangan dari seri yang berisi momen paling ikoniknya sebagai pemain. Itu terjadi pada perempat final, ketika Maradona mempermalukan tim sepak bola Inggris di lapangan, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai pembalasan puitis untuk Perang Falklands. Gol kedua Maradona dalam pertandingan itu begitu spektakuler sehingga disebut sebagai “The Goal Of The Century.” Namun, yang pertama, mungkin lebih diingat dan diabadikan dengan lebih megah: Dia menyenggol bola sedikit dengan tangan, sebuah gol yang secara teknis seharusnya dianulir. Tidak menyesal, Maradona kemudian mengatakan bahwa dia mencetak "sedikit dengan kepala Maradona dan sedikit dengan tangan Tuhan."
Kata-kata terkenal itulah yang menjadi judul drama semi-otobiografi Paolo Sorrentino, yang berlatar tahun 1980-an di Naples, masa muda sang sutradara. Di sini, Maradona tampak besar. Seluruh kota menunggu dengan napas tertahan untuk melihat apakah pemain Argentina yang perkasa itu akan bergabung dengan tim mereka. Karakter menyatakan dengan datar bahwa jika dia tidak datang untuk bermain untuk Napoli, mereka akan bunuh diri. Pria muda memperdebatkan apakah seks atau Maradona lebih baik. Yang paling manis, ketika protagonis muda kita, Fabietto Schisa (Filippo Scotti), mengalami serangan panik, kakak laki-lakinya (Marlon Joubert) memeluknya erat-erat dan berbisik, “Pikirkan tentang Maradona.”
Untuk memberikan makna lebih lanjut dari "The Hand Of God" untuk kehidupan Sorrentino dapat dianggap sebagai spoiler, meskipun banyak penggemar sutradara Italia akan menyadari apa yang terjadi padanya sebagai seorang pemuda. Film ini bekerja dari kedua perspektif, memberi bayangan cukup halus untuk tidak mengalihkan perhatian mereka yang tidak sadar tetapi perlahan-lahan meningkatkan kehancuran bagi mereka yang sadar.
Kisah Sorrentino yang meningkat tentang masa mudanya terasa lebih seperti kumpulan ingatan pribadi yang tumpang tindih daripada narasi langsung. Waktu, ruang, nada, dan masuk akal berubah dari satu adegan ke adegan lainnya. Film ini melihat pengalaman formatif ini melalui lensa berwarna mawar dari kenangan berharga—laut dan langit selalu biru paling berani, rambut wanita ditata kaku sempurna, kemegahan Napoli yang terkenal membusuk memberikan kilau baru.
Nostalgia hangat itu sebagian besar menguntungkan film tersebut, terutama saat makan siang yang dihabiskan bersama keluarga besar, menikmati bolak-balik riang di atas mozzarella segar dengan latar belakang Laut Mediterania. Kicauan cepat itu lucu; bahkan ketika seseorang meninju, mereka melakukannya dengan binar yang tak tertahankan di mata mereka. Ibu Fabietto yang nakal dan menyenangkan, Maria (Teresa Saponangelo), akan tampak seperti manifestasi cinta ibu yang sempurna—sosok Madonna yang murni—jika bukan karena waktu pertunjukan yang lucu. Dan sementara ayah anak laki-laki yang tajam dan cacat, Saverio (Toni Servillo), mungkin memiliki sikap tertentu yang terlihat ketinggalan zaman hari ini, dia juga mengungkapkan kasih sayang untuk putranya yang secara radikal bebas dari sikap maskulin. Ada chemistry dalam keluarga ini yang sama indahnya dengan pemandangan Napoli.
Di mana film berbatasan dengan kemunduran yang membosankan adalah dalam pendekatannya terhadap tubuh perempuan, yang (selain Maria) membagi dengan rapi menjadi dua kategori: memikat atau mengerikan. Sorrentino menembak wanita yang lebih besar dari jarak yang tidak manusiawi, menjadikan mereka objek ejekan; orang tidak bisa begitu saja menyalahkan ini pada nilai-nilai regresif Napoli tahun 1980-an. Tangan Tuhantidak lagi menghormati kesehatan mental mereka atau kekerasan yang dilakukan terhadap mereka—ada motif datar yang aneh dalam pendekatannya terhadap keduanya. Yang diperlakukan paling buruk dari semuanya adalah Bibi Patrizia (Luisa Ranieri) yang sangat diidam-idamkan Fabietto, diperkenalkan dalam prolog surealis dan kemudian akhirnya direduksi menjadi objek seks dalam spiral ke bawah, semakin kehilangan mimpi, kewarasan, dan kesombongannya. Fabietto (dan mungkin, dengan perluasan, Sorrentino) menganggapnya sebagai inspirasinya, tetapi film ini lebih suka menghukum wanita ini karena ketidaksopanan seksualnya.
Mungkin pandangan yang tidak dewasa tentang kewanitaan seperti itu dapat dikaitkan dengan film yang tetap kokoh dalam sudut pandang remaja laki-laki yang sedang berkembang. Namun The Hand Of God paling tidak pasti dalam menangani karakter sentralnya, yang tetap pasif, pengamat yang hampir tidak terlihat meskipun karisma bintang muda itu. Meskipun ini seolah-olah merupakan kisah dewasa, sulit untuk mengidentifikasi pertumbuhan apa pun dalam berbagai petualangan Fabietto. Satu-satunya momen kehancuran emosionalnya diambil dari belakang, dengan suara isak tangis yang tampak mencurigakan ditambahkan di postingan.

Bahkan keinginan anak laki-laki itu untuk menjadi sutradara film dinyatakan lebih eksplisit daripada yang pernah dirasakan, meskipun Sorrentino hampir tidak malu menempatkan dirinya dalam dinasti sinematik. Fellini, yang pengaruhnya sangat jelas di sini seperti di The Great Beauty , muncul sebagai sosok quasi-mitos, memilah-milah headshots seperti dewa yang tidak tertarik. Sementara itu, Antonio Capuano yang legendaris adalah Cyrano De Bergerac dari Neapolitan, berteriak di teater dan menginspirasi Fabiano muda. "Saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan," klaimnya tanpa rasa takut. "Aku bebas."
Namun film Sorrentino mungkin mendapat manfaat dari sedikit kebebasan. Ini memiliki banyak urutan berlebihan yang hebat, dengan momen-momen yang tidak memiliki tujuan yang lebih besar daripada mendaratkan satu lelucon. Di babak terakhir, Sorrentino menumpuk kesimpulan di atas kesimpulan, seolah-olah dia sedang membangun menara topi yang goyah. Namun, seperti halnya kehidupan Maradona, kilasan kecemerlangan yang terputus-putus—momen tangan Tuhan—yang tinggal bersama Anda.